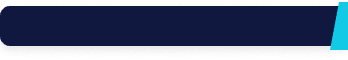Kisah Preman Paling Ditakuti di Jakarta dan Dua Jagoan Penguasa Pelabuhan Tanjung Priok
loading...

Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
PREMANISME di kawasan Tanjung Priok langsung disikat polisi pasca kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara, Kamis (10/6/2021). Tak hanya di Tanjung Priok, atas perintah Kapolri, polisi langsung melakukan operasi preman besar-besaran di berbagai wilayah di Tanah Air.
Aksi premanisme di Jakarta sejatinya sudah ada sejak zaman Belanda. Bedanya, saat zaman penjajahan para preman beraksi dengan merampok warga keturunan Belanda dan Tionghoa untuk kemudian hasilnya diberikan kepada masyarakat miskin.
Pada zaman penjajahan Kolonial Belanda, terdapat beberapa preman yang terkenal dan ditakuti warga keturunan Belanda dan Tionghoa. Mereka tidak segan-segan melukai korbannya. Pada pertengahan akhir abad 19, masyarakat Batavia mengenal Muhammad Arif alias Haji Darip yang menguasai Klender, Pulogadung, Jatinegara, hingga Bekasi.
![Kisah Preman Paling Ditakuti di Jakarta dan Dua Jagoan Penguasa Pelabuhan Tanjung Priok]()
Muhammad Arif alias Haji Darip. Foto: Dok sejarahjakarta.com
Sepak terjang kelompok Darip ini sudah kesohor sehingga pemerintahan Hindia Belanda mengiming-imingi hadiah kepada masyarakat yang bisa memberi tahu keberadaan Darip.
Dahulu target operasi yang dilakukan kelompok Darip bersifat patriotisme dan perampokan. Kelompok ini sangat selektif mengincar target operasi. Biasanya mereka mengincar orang-orang berkulit terang, seperti China dan warga keturunan Belanda.
Pertengahan abad 19 sebenarnya ada juga beberapa preman yang kesohor. Mereka adalah si Conat yang biasa berbuat kejahatan di kawasan Kebayoran Lama hingga Tangerang.
Sedangkan di kawasan pantai Utara, ada preman bernama Angkri yang menguasai kawasan Marunda, Tanjung Priok, dan Ancol. Keduanya sama-sama merampok untuk diberikan ke warga miskin. Sepak terjang Angkri hampir sama dengan si Pitung yang sudah melegenda di Marunda. Kendati begitu belum ada catatan yang mengaitkan kedua orang ini.
Pasca kemerdekaan Indonesia, Jakarta yang menjadi Ibu Kota Negara memasuki zaman yang rawan dengan kekerasan dan tindak kriminal. Sebagian besar pelakunya merupakan eks pejuang laskar yang kehilangan pekerjaan karena revolusi telah usai. Mereka yang tidak terakomodir dalam institusi resmi militer memilih “dunia kekerasan” untuk menyambung hidup.
Daerah-daerah ekonomi seperti Senen, Meester Cornelis, Tanah Abang, dan Tanjung Priok, menjadi tempat menyandarkan kebutuhan hidup. Mereka menjajakan diri sebagai penjaga keamanan, centeng alias jagoan.
Daerah-daerah ekonomi itu menjadi lahan perebutan kekuasaan, baik antarindividu maupun antarorganisasi pengelola keamanan. Hal ini yang menjadi penyebab utama daerah tersebut dinamakan oleh masyarakat umum waktu itu sebagai daerah onderwereld (dunia hitam) yang dianggap seram dan menakutkan.
Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama Kota Jakarta menjadi salah satu lumbung ekonomi yang dipenuhi para jagoan. Mereka berangkat dari berbagai macam latar belakang etnis. Secara umum tidak ada penguasa tunggal dari latar belakang etnis dalam dunia kekerasan di kota Jakarta.
Dikutip dari situs sejarahjakarta.com, dua etnis yang pernah eksis dalam percaturan onderwereld di Jakarta Utara atau di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya adalah etnis Bugis dan Banten. Salah satu nama jagoan yang legendaris sebagai penguasa Pelabuhan Tanjung Priok hingga akhir tahun 50-an adalah Lagoa, tokoh masyarakat Bugis yang bernama asli Labuang De Passore. Selain sebagai tokoh masyarakat, Lagoa juga dikenal sebagai seorang jago yang merangkap menjadi mandor pelabuhan.
![Kisah Preman Paling Ditakuti di Jakarta dan Dua Jagoan Penguasa Pelabuhan Tanjung Priok]()
Labuang De Passore. Foto: Dok sejarahjakarta.com
Para buruh menganggap mandor sebagai tokoh jago yang dituakan. Bahkan dianggap sebagai pemimpin dari kalangan etnisnya. Hal ini pula yang dialami Lagoa sewaktu menjadi Mandor Pelabuhan Tanjung Priok. Tidak hanya di kalangan etnis Bugis-Makassar saja, Lagoa juga dipandang sebagai tokoh masyarakat yang punya kharisma oleh etnis lain yang ada di seputar Pelabuhan Tanjung Priok.
Di Pelabuhan Tanjung Priok juga terdapat tokoh lain berasal dari etnis Banten yang berprofesi sebagai mandor, yaitu Haji Tjitra yang bernama lengkap Haji Tjitra bin Kidang. Namanya sudah kondang sebagai penguasa penguasa Pelabuhan Tanjung Priok sejak akhir tahun 1920-an yang direbutnya melalui pertarungan sengit dengan jago yang juga berasal dari Banten.
Kedatangan Lagoa di Pelabuhan Tanjung Priok sedikit banyak mengusik “pendaringan” Haji Tjitra bin Kidang. Sebab itu perseteruan kedua tokoh ini legendaris di Pelabuhan Tanjung Priok. Kerap kerusuhan sering terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok karena perebutan kekuasaan dari dua mandor berbeda etnis ini, tidak sekali dua kali mengakibatkan korban nyawa yang menghiasi berita di koran-koran Ibu Kota kala itu.
Cerita kedua tokoh Mandor Pelabuhan Tanjung Priok dari berbeda etnis ini meski diawali dengan perseteruan namun berakhir dengan harmonis. Keduanya mampu menjadi tokoh perdamaian peredam konflik yang pernah terjadi di antara etnis Bugis-Makassar dan Banten, bahkan dengan komunitas etnis lainnya.
Puncak kedamaian ditandai dengan diangkatnya Lagoa menjadi menantu oleh Haji Tjitra bin Kidang sebagai wujud perdamaian dan persaudaraan antara etnis Banten dan Bugis-Makassar di Tanjung Priok.
Pelabuhan Tanjung Priok sebagai daerah dengan penuh kekerasan terus berlanjut sepeninggal mereka berdua, bahkan meluas hingga ke luar daerah pelabuhan. Hingga di pertengahan tahun 60-an terjadi konflik besar yang memakan banyak korban jiwa antar beberapa etnis penguasa daerah kekerasan di Tanjung Priok.
Bahkan sampai harus melibatkan pejabat tinggi militer yang juga tokoh masyarakat Bugis saat itu, Brigjend. TNI Andi Muhammad Jusuf Amir dan Kol TNI Ahmad Daeng Setoedjoe untuk mendamaikan. Sampai kini, Tanjung Priok masih dikenal sebagai "daerah keras" meski tidak lagi sekeras dulu.
Aksi premanisme di Jakarta sejatinya sudah ada sejak zaman Belanda. Bedanya, saat zaman penjajahan para preman beraksi dengan merampok warga keturunan Belanda dan Tionghoa untuk kemudian hasilnya diberikan kepada masyarakat miskin.
Pada zaman penjajahan Kolonial Belanda, terdapat beberapa preman yang terkenal dan ditakuti warga keturunan Belanda dan Tionghoa. Mereka tidak segan-segan melukai korbannya. Pada pertengahan akhir abad 19, masyarakat Batavia mengenal Muhammad Arif alias Haji Darip yang menguasai Klender, Pulogadung, Jatinegara, hingga Bekasi.

Muhammad Arif alias Haji Darip. Foto: Dok sejarahjakarta.com
Sepak terjang kelompok Darip ini sudah kesohor sehingga pemerintahan Hindia Belanda mengiming-imingi hadiah kepada masyarakat yang bisa memberi tahu keberadaan Darip.
Dahulu target operasi yang dilakukan kelompok Darip bersifat patriotisme dan perampokan. Kelompok ini sangat selektif mengincar target operasi. Biasanya mereka mengincar orang-orang berkulit terang, seperti China dan warga keturunan Belanda.
Pertengahan abad 19 sebenarnya ada juga beberapa preman yang kesohor. Mereka adalah si Conat yang biasa berbuat kejahatan di kawasan Kebayoran Lama hingga Tangerang.
Sedangkan di kawasan pantai Utara, ada preman bernama Angkri yang menguasai kawasan Marunda, Tanjung Priok, dan Ancol. Keduanya sama-sama merampok untuk diberikan ke warga miskin. Sepak terjang Angkri hampir sama dengan si Pitung yang sudah melegenda di Marunda. Kendati begitu belum ada catatan yang mengaitkan kedua orang ini.
Pasca kemerdekaan Indonesia, Jakarta yang menjadi Ibu Kota Negara memasuki zaman yang rawan dengan kekerasan dan tindak kriminal. Sebagian besar pelakunya merupakan eks pejuang laskar yang kehilangan pekerjaan karena revolusi telah usai. Mereka yang tidak terakomodir dalam institusi resmi militer memilih “dunia kekerasan” untuk menyambung hidup.
Daerah-daerah ekonomi seperti Senen, Meester Cornelis, Tanah Abang, dan Tanjung Priok, menjadi tempat menyandarkan kebutuhan hidup. Mereka menjajakan diri sebagai penjaga keamanan, centeng alias jagoan.
Daerah-daerah ekonomi itu menjadi lahan perebutan kekuasaan, baik antarindividu maupun antarorganisasi pengelola keamanan. Hal ini yang menjadi penyebab utama daerah tersebut dinamakan oleh masyarakat umum waktu itu sebagai daerah onderwereld (dunia hitam) yang dianggap seram dan menakutkan.
Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama Kota Jakarta menjadi salah satu lumbung ekonomi yang dipenuhi para jagoan. Mereka berangkat dari berbagai macam latar belakang etnis. Secara umum tidak ada penguasa tunggal dari latar belakang etnis dalam dunia kekerasan di kota Jakarta.
Dikutip dari situs sejarahjakarta.com, dua etnis yang pernah eksis dalam percaturan onderwereld di Jakarta Utara atau di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya adalah etnis Bugis dan Banten. Salah satu nama jagoan yang legendaris sebagai penguasa Pelabuhan Tanjung Priok hingga akhir tahun 50-an adalah Lagoa, tokoh masyarakat Bugis yang bernama asli Labuang De Passore. Selain sebagai tokoh masyarakat, Lagoa juga dikenal sebagai seorang jago yang merangkap menjadi mandor pelabuhan.

Labuang De Passore. Foto: Dok sejarahjakarta.com
Para buruh menganggap mandor sebagai tokoh jago yang dituakan. Bahkan dianggap sebagai pemimpin dari kalangan etnisnya. Hal ini pula yang dialami Lagoa sewaktu menjadi Mandor Pelabuhan Tanjung Priok. Tidak hanya di kalangan etnis Bugis-Makassar saja, Lagoa juga dipandang sebagai tokoh masyarakat yang punya kharisma oleh etnis lain yang ada di seputar Pelabuhan Tanjung Priok.
Di Pelabuhan Tanjung Priok juga terdapat tokoh lain berasal dari etnis Banten yang berprofesi sebagai mandor, yaitu Haji Tjitra yang bernama lengkap Haji Tjitra bin Kidang. Namanya sudah kondang sebagai penguasa penguasa Pelabuhan Tanjung Priok sejak akhir tahun 1920-an yang direbutnya melalui pertarungan sengit dengan jago yang juga berasal dari Banten.
Kedatangan Lagoa di Pelabuhan Tanjung Priok sedikit banyak mengusik “pendaringan” Haji Tjitra bin Kidang. Sebab itu perseteruan kedua tokoh ini legendaris di Pelabuhan Tanjung Priok. Kerap kerusuhan sering terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok karena perebutan kekuasaan dari dua mandor berbeda etnis ini, tidak sekali dua kali mengakibatkan korban nyawa yang menghiasi berita di koran-koran Ibu Kota kala itu.
Cerita kedua tokoh Mandor Pelabuhan Tanjung Priok dari berbeda etnis ini meski diawali dengan perseteruan namun berakhir dengan harmonis. Keduanya mampu menjadi tokoh perdamaian peredam konflik yang pernah terjadi di antara etnis Bugis-Makassar dan Banten, bahkan dengan komunitas etnis lainnya.
Puncak kedamaian ditandai dengan diangkatnya Lagoa menjadi menantu oleh Haji Tjitra bin Kidang sebagai wujud perdamaian dan persaudaraan antara etnis Banten dan Bugis-Makassar di Tanjung Priok.
Pelabuhan Tanjung Priok sebagai daerah dengan penuh kekerasan terus berlanjut sepeninggal mereka berdua, bahkan meluas hingga ke luar daerah pelabuhan. Hingga di pertengahan tahun 60-an terjadi konflik besar yang memakan banyak korban jiwa antar beberapa etnis penguasa daerah kekerasan di Tanjung Priok.
Bahkan sampai harus melibatkan pejabat tinggi militer yang juga tokoh masyarakat Bugis saat itu, Brigjend. TNI Andi Muhammad Jusuf Amir dan Kol TNI Ahmad Daeng Setoedjoe untuk mendamaikan. Sampai kini, Tanjung Priok masih dikenal sebagai "daerah keras" meski tidak lagi sekeras dulu.
(thm)