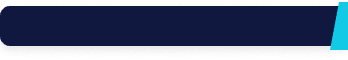Jejak Kembang Lumpang dari Kampung Cengkareng

Jejak Kembang Lumpang dari Kampung Cengkareng
A
A
A
MUNGKIN sekarang ini banyak warga Jakarta yang sangat asing dengan sebutan kembang lumpang. Padahal sebelum jaman kemerdekaan, tak sedikit kaum perempuan yang menjadi kembang lumpang untuk membantu perekonomian keluarganya.
Kembang lumpang sendiri merupakan sebutan bagi kaum perempuan yang berprofesi sebagai penumbuk padi. Biasanya ini dilakukan oleh wanita kampung miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Mereka terpaksa menggunakan kekuatan tangan untuk mengubah padi menjadi beras karena tidak memiliki sawah untuk ditanami padi. Apalagi pada jaman itu, lapangan pekerjaan memang sedikit dan sekalinya ada itu hanyalah pekerjaan kasar atau buruh.
Mengenai sebutan kembang lumpang, nama kembang sendiri diambil karena pekerjanya adalah perempuan. Sedangkan lumpang adalah alat untuk menumbuk yang biasa berpasangan dengan alu. Jadilah kuli penumbuk padi ini disebut kembang lumpang.
Menurut penuturan Nyai Nipah mantan kembang lumpang dari Kampung Cengkareng (sekarang kelurahan Cengkareng), masa keemasan kembang lumpang terjadi ketika daerah Cengkareng masih banyak terdapat sawah.
Belum adanya teknologi, membuat wanita berusia 75 tahun ini dan puluhan kembang lumpang lainnya menjadi pemutar roda perekonomian kampung pascapanen padi. Maklum saja, juragan tanah dan tengkulak padi memerlukan beras untuk dijual atau dikonsumsi.
Upah yang didapat kembang lumpang atau kuli penumbuk padi memang tidak banyak. Dari setiap sepuluh liter beras yang dihasilkan, mereka mendapat upah dua liter. Namun bagi wanita kampung miskin, semua itu sudah cukup karena mereka bisa makan nasi.
Satu hari kembang lumpang mampu menumbuk 90 liter gabah kering untuk menghasilkan 40 liter beras. Dengan kemampuan tersebut, kembang lumpang mampu membawa pulang delapan liter beras setiap hari. Disamping beras, ada juga hasil lain berupa menir (beras kecil-kecil) dan dedak.
Untuk menir, biasanya para kembang lumpang langsung menghaluskannya untuk dijadikan penganan teman minum kopi. Menir yang dihaluskan menjadi tepung, dibungkus daun pisang dan dibakar menjadi kue. Sedangkan dedak yang dihasilkan dijadikan makanan ternak.
Namun sekitar tahun 1970-an, periuk nasi para kembang lumpang ini terusik dengan kehadiran seorang petani kaya dari Kampung Bulak (kini Kampung Bulakteko, Kelurahan Kalideres). Petani kaya ini membeli sebuah mesin giling gabah dengan tenaga mesin.
Mesin penggiling padi yang bisa bekerja siang-malam ternyata juga menarik minat tuan tanah China di Kampung Lele (sekarang Kampung Rawa Lele, kelurahan Kalideres) untuk memilikinya. Lambat laun, kedatangan mesin itu mengubah cara petani mengolah padi menjadi beras.
Sejak kedatangan mesih penggiling padi itu, di kampung Cengkareng mulai berkurang suara alu beradu dengan lumpang. Gantinya, deru mesih giling yang cukup berisik itu, seakan tak pernah berhenti siang-malam.
Sedikit demi sedikit, kembang lumpang mulai dilupakan. Petani kaya dan tengkulak gabah mulai beralih ke mesin giling tersebut. Sejak itu, karir Nyai Nipah dan puluhan kembang lumpang lainnya di tanah Cengkareng berakhir.
(Sumber: diolah dari anakmandorbuang.blogspot.com)
Kembang lumpang sendiri merupakan sebutan bagi kaum perempuan yang berprofesi sebagai penumbuk padi. Biasanya ini dilakukan oleh wanita kampung miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Mereka terpaksa menggunakan kekuatan tangan untuk mengubah padi menjadi beras karena tidak memiliki sawah untuk ditanami padi. Apalagi pada jaman itu, lapangan pekerjaan memang sedikit dan sekalinya ada itu hanyalah pekerjaan kasar atau buruh.
Mengenai sebutan kembang lumpang, nama kembang sendiri diambil karena pekerjanya adalah perempuan. Sedangkan lumpang adalah alat untuk menumbuk yang biasa berpasangan dengan alu. Jadilah kuli penumbuk padi ini disebut kembang lumpang.
Menurut penuturan Nyai Nipah mantan kembang lumpang dari Kampung Cengkareng (sekarang kelurahan Cengkareng), masa keemasan kembang lumpang terjadi ketika daerah Cengkareng masih banyak terdapat sawah.
Belum adanya teknologi, membuat wanita berusia 75 tahun ini dan puluhan kembang lumpang lainnya menjadi pemutar roda perekonomian kampung pascapanen padi. Maklum saja, juragan tanah dan tengkulak padi memerlukan beras untuk dijual atau dikonsumsi.
Upah yang didapat kembang lumpang atau kuli penumbuk padi memang tidak banyak. Dari setiap sepuluh liter beras yang dihasilkan, mereka mendapat upah dua liter. Namun bagi wanita kampung miskin, semua itu sudah cukup karena mereka bisa makan nasi.
Satu hari kembang lumpang mampu menumbuk 90 liter gabah kering untuk menghasilkan 40 liter beras. Dengan kemampuan tersebut, kembang lumpang mampu membawa pulang delapan liter beras setiap hari. Disamping beras, ada juga hasil lain berupa menir (beras kecil-kecil) dan dedak.
Untuk menir, biasanya para kembang lumpang langsung menghaluskannya untuk dijadikan penganan teman minum kopi. Menir yang dihaluskan menjadi tepung, dibungkus daun pisang dan dibakar menjadi kue. Sedangkan dedak yang dihasilkan dijadikan makanan ternak.
Namun sekitar tahun 1970-an, periuk nasi para kembang lumpang ini terusik dengan kehadiran seorang petani kaya dari Kampung Bulak (kini Kampung Bulakteko, Kelurahan Kalideres). Petani kaya ini membeli sebuah mesin giling gabah dengan tenaga mesin.
Mesin penggiling padi yang bisa bekerja siang-malam ternyata juga menarik minat tuan tanah China di Kampung Lele (sekarang Kampung Rawa Lele, kelurahan Kalideres) untuk memilikinya. Lambat laun, kedatangan mesin itu mengubah cara petani mengolah padi menjadi beras.
Sejak kedatangan mesih penggiling padi itu, di kampung Cengkareng mulai berkurang suara alu beradu dengan lumpang. Gantinya, deru mesih giling yang cukup berisik itu, seakan tak pernah berhenti siang-malam.
Sedikit demi sedikit, kembang lumpang mulai dilupakan. Petani kaya dan tengkulak gabah mulai beralih ke mesin giling tersebut. Sejak itu, karir Nyai Nipah dan puluhan kembang lumpang lainnya di tanah Cengkareng berakhir.
(Sumber: diolah dari anakmandorbuang.blogspot.com)
(ysw)