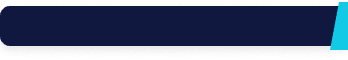Vokasi UI: Pemikiran Kritis Benteng Melawan Radikalisme

Vokasi UI: Pemikiran Kritis Benteng Melawan Radikalisme
A
A
A
DEPOK - Pemikiran kritis merupakan salah satu benteng untuk melawan radikalisme. Namun untuk berfikir kritis juga menjadi sulit karena perubahan kemajuan teknologi yang terjadi tiap detik.
Bagaimana tidak, dalam 60 detik saja terdapat 60 blog baru, 98 ribu tweets, 600 video baru di Youtube, 13 ribu aplikasi iPhone yang di-download, 695 ribu status Facebook yang diupdate; 695 ribu pencarian dan lain-lain. "Kondisi yang super bising dan aktif ini berpeluang menumpulkan daya kritis," ujar Kepala Program Studi Humas Vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati saat seminar bertemakan Melawan Radikalisme & Diskriminasi, yang digelar di Pusat Kebudayaan Soka Gakai Indonesia, Pameran Sutra Bunga Teratai, Minggu (20/10/2019).
Dikatakan dia, berbagai informasi yang masuk, tidak hanya menyita waktu audiens, namun menguras kepercayaan masyarakat terhadap banyak institusi, khususnya media dan pemerintah. Situasi ini mengakibatkan banyaknya informasi negatif seperti misinformasi, disinformasi dan hoaks yang menyerbu media.
"Yang cukup tragis, media (konvensional) justru menjadi salah satu institusi yang paling tidak dipercaya di 22 negara dari 28 negara yang disurvei (Fray, 2019)," ucapnya.
Penerima Australia Awards 2019 itu menambahkan, ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan media (konvensional), yang kemudian semakin memperlemah nalar ialah ternyata riset menemukan 1 dari 2 orang akan mendukung politisi yang dia percaya, meskipun dia mengetahui bahwa politisi itu membesar-besarkan kebenaran.
Tidak hanya itu 53% individu tidak mau mendengarkan orang atau organisasi yang bertentangan dengan mereka, serta 4 kali lebih besar mengabaikan segala informasi yang tidak sesuai dengan keyakinannya. "Sehingga 52% respondens menyatakan bahwa mereka nyaris tidak akan mengubah pendapat mereka (Fray, 2019)," tambahnya.
Belajar dari Australia, kata dia, kemampuan berpikir kritis bukan sesuatu yang tiba-tiba terbentuk di dalam masyarakat. Namun dibutuhkan upaya sistematis membangun ekosistem kritis, seperti perpustakaan. Perpustakaan dirancang sebagai arena penyelesain masalah (problem solving) bagi masyarakat. Diantaranya bagaimana perpustakaan membantu masyarakat untuk tidak takut dengan teknologi, tapi justru mampu mengadopsi dan beradaptasi dengan perubahan.
"Perpustakaan bukan hanya tempat meminjam dan membaca buku, tetapi menjadi pusat mengembangkan kreativitas, membangun inovasi, menyelesaikan masalah, meningkatkan spirit dan aktivitas kewirausahaan," tukasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, perpustakaan bersifat hybrid, yaitu menyediakan kebutuhan offline dan online. Perpustakaan menyediakan 2T (teknologi dan training), yang seluruhnya diberikan secara gratis. Pelatihan teknologi yang diberikan gratis meliputi lima area yaitu core skills, extra skills, digital devices, library rewources dan tech kids.
Contoh training yang diberikan ialah computer skills 1 dan 2; email skills 1 dan 2; internet skills; ebay basic; simple photo editing; android & ipad skills; dash and dots robots, dan sebagainya. Australia merancang program-program pelatihan di perpustakaan, untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang mengkoneksikan individu yang satu dengan yang lain, sehingga dengan jaringan baru ini, masyarakat dapat terbantu untuk mendapatkan ide-ide dan membentuk komunitas, yang kemudian secara nyata, berbisnis misalnya.
"Ketika masyarakat sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesibukan, mereka akan fokus untuk melakukan hal-hal produktif. Selain itu, mereka juga sudah terbiasa melakukan langkah-langkah rasional, karena senantiasa dapat mengakses fasilitas gratis dan terdepan yang diberikan oleh perpustakaan," katanya.
Di tempat yang sama, Founder of Hadassah Indonesia Monique Rijkers menyampaikan bahwa sering kali terjadi persekusi yang didorong oleh ketidaktahuan dan ketidapahaman. Padahal keduanya ialah merupakan hal utama untuk mencegah lahirnya pemahaman-pemahaman radikal. “Yang orang perlu ingat ialah kita tidak bisa memilih lahir sebagai apa. Dan semua orang punya hak asasi manusia yang sama, yang dilindungi secara hukum," katanya.
Bagaimana tidak, dalam 60 detik saja terdapat 60 blog baru, 98 ribu tweets, 600 video baru di Youtube, 13 ribu aplikasi iPhone yang di-download, 695 ribu status Facebook yang diupdate; 695 ribu pencarian dan lain-lain. "Kondisi yang super bising dan aktif ini berpeluang menumpulkan daya kritis," ujar Kepala Program Studi Humas Vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati saat seminar bertemakan Melawan Radikalisme & Diskriminasi, yang digelar di Pusat Kebudayaan Soka Gakai Indonesia, Pameran Sutra Bunga Teratai, Minggu (20/10/2019).
Dikatakan dia, berbagai informasi yang masuk, tidak hanya menyita waktu audiens, namun menguras kepercayaan masyarakat terhadap banyak institusi, khususnya media dan pemerintah. Situasi ini mengakibatkan banyaknya informasi negatif seperti misinformasi, disinformasi dan hoaks yang menyerbu media.
"Yang cukup tragis, media (konvensional) justru menjadi salah satu institusi yang paling tidak dipercaya di 22 negara dari 28 negara yang disurvei (Fray, 2019)," ucapnya.
Penerima Australia Awards 2019 itu menambahkan, ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan media (konvensional), yang kemudian semakin memperlemah nalar ialah ternyata riset menemukan 1 dari 2 orang akan mendukung politisi yang dia percaya, meskipun dia mengetahui bahwa politisi itu membesar-besarkan kebenaran.
Tidak hanya itu 53% individu tidak mau mendengarkan orang atau organisasi yang bertentangan dengan mereka, serta 4 kali lebih besar mengabaikan segala informasi yang tidak sesuai dengan keyakinannya. "Sehingga 52% respondens menyatakan bahwa mereka nyaris tidak akan mengubah pendapat mereka (Fray, 2019)," tambahnya.
Belajar dari Australia, kata dia, kemampuan berpikir kritis bukan sesuatu yang tiba-tiba terbentuk di dalam masyarakat. Namun dibutuhkan upaya sistematis membangun ekosistem kritis, seperti perpustakaan. Perpustakaan dirancang sebagai arena penyelesain masalah (problem solving) bagi masyarakat. Diantaranya bagaimana perpustakaan membantu masyarakat untuk tidak takut dengan teknologi, tapi justru mampu mengadopsi dan beradaptasi dengan perubahan.
"Perpustakaan bukan hanya tempat meminjam dan membaca buku, tetapi menjadi pusat mengembangkan kreativitas, membangun inovasi, menyelesaikan masalah, meningkatkan spirit dan aktivitas kewirausahaan," tukasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, perpustakaan bersifat hybrid, yaitu menyediakan kebutuhan offline dan online. Perpustakaan menyediakan 2T (teknologi dan training), yang seluruhnya diberikan secara gratis. Pelatihan teknologi yang diberikan gratis meliputi lima area yaitu core skills, extra skills, digital devices, library rewources dan tech kids.
Contoh training yang diberikan ialah computer skills 1 dan 2; email skills 1 dan 2; internet skills; ebay basic; simple photo editing; android & ipad skills; dash and dots robots, dan sebagainya. Australia merancang program-program pelatihan di perpustakaan, untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang mengkoneksikan individu yang satu dengan yang lain, sehingga dengan jaringan baru ini, masyarakat dapat terbantu untuk mendapatkan ide-ide dan membentuk komunitas, yang kemudian secara nyata, berbisnis misalnya.
"Ketika masyarakat sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesibukan, mereka akan fokus untuk melakukan hal-hal produktif. Selain itu, mereka juga sudah terbiasa melakukan langkah-langkah rasional, karena senantiasa dapat mengakses fasilitas gratis dan terdepan yang diberikan oleh perpustakaan," katanya.
Di tempat yang sama, Founder of Hadassah Indonesia Monique Rijkers menyampaikan bahwa sering kali terjadi persekusi yang didorong oleh ketidaktahuan dan ketidapahaman. Padahal keduanya ialah merupakan hal utama untuk mencegah lahirnya pemahaman-pemahaman radikal. “Yang orang perlu ingat ialah kita tidak bisa memilih lahir sebagai apa. Dan semua orang punya hak asasi manusia yang sama, yang dilindungi secara hukum," katanya.
(thm)