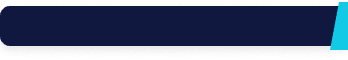Peneliti UI: Literasi Digital Diperlukan untuk Mencegah Hoaks

Peneliti UI: Literasi Digital Diperlukan untuk Mencegah Hoaks
A
A
A
DEPOK - Sebanyak 24 orang penerima penghargaan Australian Awards, mengikuti sekolah Democratic Resilience–Digital & Media Literacy di Queensland University of Technology (QUT). Salah satunya adalah peneliti Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati. Mereka dilatih oleh para ahli di bidang komunikasi digital dan media, di jurusan dengan peringkat 15 terbaik di dunia.
Kelas pertama dibuka dengan presentasi oleh Fiona Suwana tentang Building Digital Media and Information Literacy; Axel Bruns: ‘The Challenge of Fake News; Angela Romano: 5RS : Rights, Respect, Responsibility, Reasoning and Resilience.
Literasi digital dibutuhkan untuk membantu individu dan keluarga agar dapat melindungi dirinya sendiri dari konten dan komunikasi yang tidak diinginkan di dunia digital. "Upaya mendidik masyarakat agar memiliki kompetensi digital dan media bukanlah hal yang mudah, khususnya pada aspek pendidikan, digital, komunitas dan politik," kata Devie, salah satu penerima penghargaan, Kamis (26/9/2019).
Data di Indonesia menunjukkan bahwa populasi penggunaan perangkat elektronik terbesar ialah televisi 95% dan telepon genggam mencapai 91%. Kondisi ini tercipta diantaranya karena aspek geografis yang luas di Indonesia, sehingga dukungan infrastruktur digital belum sepenuhnya menjadi konsumsi utama masyarakat di berbagai wilayah. Selain itu, generasi yang lebih senior, akan lebih mudah untuk mengkonsumsi televisi.
"Meskipun demikian, mengingat kehadiran teknologi digital yang bersifat personal dan dapat diakses dalam 24 jam sehari, membuat dampak dari informasi yang dikonsumsi melalui perangkat digital akan lebih mudah, cepat dan murah untuk dikonsumsi dan diproduksi oleh siapapun," kata Ketua Program Studi Vokasi Humas UI itu.
Dia menuturkan, dalam konteks Indonesia, tantangannya ada tiga yaitu masyarakat yang plural, latar belakang kultural, dan kondisi struktural. Pluralitas wilayah, ekonomi, suku, agama, ras, mendorong kesenjangan penetrasi digital. Sedangkan secara kultural, salah satunya masyarakat Indonesia adalah masyarakat pendongeng (oral culture society), yang membuat kurangnya upaya menggali dan mengkonfirmasi informasi secara mendalam.
Struktur kebijakan pendidikan yang masih mengedepankan target-target kuantitatif seperti jumlah hapalan, bukan pada aspek kualitas seperti kemampuan reflektif dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan iklim. Di Indonesia, sudah banyak inisiatif komunitas untuk membantu pemerintah dalam mendorong terciptanya literasi digital.
"Dampak negatif dari rendahnya literasi digital di antaranya ialah konsumsi tayangan kekerasan, pornografi, kecanduan game, media sosial dan penyebaran hoax yang mampu memecah belah bangsa, sebagaimana residu dari kontestasi politik di Indonesia semenjak 2017 lalu," ucapnya.
Polarisasi di dalam masyarakat akibat penyebaran berita bohong memang akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menyatukan kembali masyarakat. Berita bohong terciptanya secara organik dan non-organik. Kecemasan masyarakat misalnya melihat situasi demo, akan mendorong masyarakat dengan mudah meneruskan infromasi apapun tentang demo, karena ketulusan masyarakat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Namun, kondisi non-organik karena insentif ekonomi berupa uang oleh platform yang memberikan dana Rp350 ribu per 1000 likes, tentu saja mendorong orang memproduksi informasi yang belum tentu benar, asalkan viral.
"Tidak hanya itu, kepentingan politik, sebagaimana yang didemonstrasikan oleh Donald Trump yang justru mengatakan berita bohong ialah ketika berita tersebut adalah berita yang tidak sesuai dengan keinginannya, mendorong klaim kebenaran yang memecah masyarakat," tutupnya.
Kelas pertama dibuka dengan presentasi oleh Fiona Suwana tentang Building Digital Media and Information Literacy; Axel Bruns: ‘The Challenge of Fake News; Angela Romano: 5RS : Rights, Respect, Responsibility, Reasoning and Resilience.
Literasi digital dibutuhkan untuk membantu individu dan keluarga agar dapat melindungi dirinya sendiri dari konten dan komunikasi yang tidak diinginkan di dunia digital. "Upaya mendidik masyarakat agar memiliki kompetensi digital dan media bukanlah hal yang mudah, khususnya pada aspek pendidikan, digital, komunitas dan politik," kata Devie, salah satu penerima penghargaan, Kamis (26/9/2019).
Data di Indonesia menunjukkan bahwa populasi penggunaan perangkat elektronik terbesar ialah televisi 95% dan telepon genggam mencapai 91%. Kondisi ini tercipta diantaranya karena aspek geografis yang luas di Indonesia, sehingga dukungan infrastruktur digital belum sepenuhnya menjadi konsumsi utama masyarakat di berbagai wilayah. Selain itu, generasi yang lebih senior, akan lebih mudah untuk mengkonsumsi televisi.
"Meskipun demikian, mengingat kehadiran teknologi digital yang bersifat personal dan dapat diakses dalam 24 jam sehari, membuat dampak dari informasi yang dikonsumsi melalui perangkat digital akan lebih mudah, cepat dan murah untuk dikonsumsi dan diproduksi oleh siapapun," kata Ketua Program Studi Vokasi Humas UI itu.
Dia menuturkan, dalam konteks Indonesia, tantangannya ada tiga yaitu masyarakat yang plural, latar belakang kultural, dan kondisi struktural. Pluralitas wilayah, ekonomi, suku, agama, ras, mendorong kesenjangan penetrasi digital. Sedangkan secara kultural, salah satunya masyarakat Indonesia adalah masyarakat pendongeng (oral culture society), yang membuat kurangnya upaya menggali dan mengkonfirmasi informasi secara mendalam.
Struktur kebijakan pendidikan yang masih mengedepankan target-target kuantitatif seperti jumlah hapalan, bukan pada aspek kualitas seperti kemampuan reflektif dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan iklim. Di Indonesia, sudah banyak inisiatif komunitas untuk membantu pemerintah dalam mendorong terciptanya literasi digital.
"Dampak negatif dari rendahnya literasi digital di antaranya ialah konsumsi tayangan kekerasan, pornografi, kecanduan game, media sosial dan penyebaran hoax yang mampu memecah belah bangsa, sebagaimana residu dari kontestasi politik di Indonesia semenjak 2017 lalu," ucapnya.
Polarisasi di dalam masyarakat akibat penyebaran berita bohong memang akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menyatukan kembali masyarakat. Berita bohong terciptanya secara organik dan non-organik. Kecemasan masyarakat misalnya melihat situasi demo, akan mendorong masyarakat dengan mudah meneruskan infromasi apapun tentang demo, karena ketulusan masyarakat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Namun, kondisi non-organik karena insentif ekonomi berupa uang oleh platform yang memberikan dana Rp350 ribu per 1000 likes, tentu saja mendorong orang memproduksi informasi yang belum tentu benar, asalkan viral.
"Tidak hanya itu, kepentingan politik, sebagaimana yang didemonstrasikan oleh Donald Trump yang justru mengatakan berita bohong ialah ketika berita tersebut adalah berita yang tidak sesuai dengan keinginannya, mendorong klaim kebenaran yang memecah masyarakat," tutupnya.
(thm)